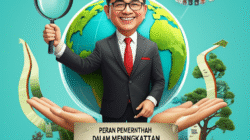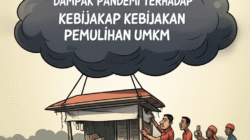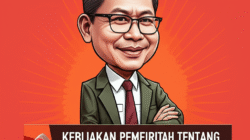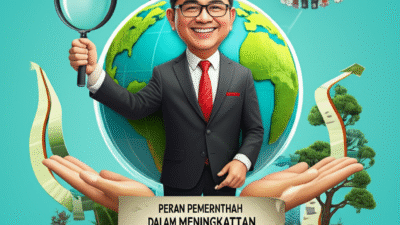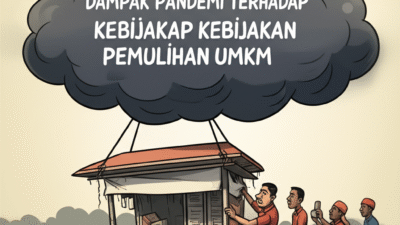Pedang Keadilan atau Pelanggaran Hak Asasi? Analisis Yuridis Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
Pendahuluan
Hukuman mati, sebagai bentuk pidana paling ekstrem, selalu menjadi topik yang memicu perdebatan sengit di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mempertahankan dan sesekali melaksanakan hukuman mati seringkali dihadapkan pada kritik tajam dari pegiat hak asasi manusia, namun di sisi lain mendapat dukungan kuat dari sebagian masyarakat yang mendambakan keadilan retributif dan efek jera. Analisis yuridis terhadap kebijakan ini menjadi krusial untuk memahami landasan hukum, implikasi konstitusional, serta posisi Indonesia dalam konstelasi hukum internasional. Artikel ini akan mengupas tuntas aspek-aspek tersebut untuk memberikan gambaran yang komprehensif.
I. Landasan Yuridis Hukuman Mati di Indonesia
Hukuman mati masih diakui dan diatur dalam sistem hukum positif Indonesia. Keberadaannya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958) mengatur hukuman mati untuk beberapa tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), kejahatan terhadap keamanan negara (misalnya Pasal 104, 111, 124), dan tindak pidana terkait perang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), terdapat perubahan signifikan meskipun hukuman mati tidak dihapus. KUHP Baru memperkenalkan "pidana mati alternatif" dengan masa percobaan 10 tahun. Artinya, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan penyesalan atau berperilaku baik selama masa percobaan. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju "abolisionis de facto" atau setidaknya mengurangi pelaksanaan hukuman mati.
- Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang paling sering menerapkan hukuman mati, khususnya bagi pelaku kejahatan narkotika kelas kakap seperti produsen, importir, atau pengedar narkotika dalam jumlah besar. Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak generasi bangsa.
- Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur ancaman hukuman mati bagi pelaku terorisme yang mengakibatkan kematian atau luka berat, mengingat dampak masif dan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Meskipun jarang diterapkan, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hukuman mati, terutama jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu (misalnya saat bencana alam atau krisis ekonomi) yang memberatkan.
Keberadaan landasan hukum ini menunjukkan bahwa secara legislatif, negara Indonesia masih mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem pemidanaannya.
II. Dimensi Konstitusional Hukuman Mati
Salah satu perdebatan paling fundamental mengenai hukuman mati di Indonesia adalah hubungannya dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Konstitusi.
-
Hak untuk Hidup dan Batasan Konstitusional: Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya (misalnya Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 107/PUU-X/2012) telah menegaskan bahwa hak untuk hidup bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi oleh undang-undang. MK berpendapat bahwa pembatasan tersebut, termasuk pemberlakuan hukuman mati, adalah sah sepanjang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia orang lain (misalnya korban kejahatan) dan demi kepentingan negara, serta diatur secara limitatif dalam undang-undang. MK melihat hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak yang diizinkan oleh Konstitusi, bukan sebagai pelanggaran hak yang mutlak. -
Mekanisme Perlindungan Konstitusional: Meskipun MK mengizinkan hukuman mati, putusan-putusan tersebut juga menekankan pentingnya jaminan proses hukum yang adil (due process of law) dan adanya jalur hukum luar biasa seperti upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), hingga grasi dari Presiden. Adanya jalur-jalur ini dianggap sebagai mekanisme perlindungan untuk meminimalisir kesalahan dan memberikan kesempatan terakhir bagi terpidana.
III. Perspektif Hukum Internasional
Kebijakan hukuman mati di Indonesia seringkali disorot dari kacamata hukum hak asasi manusia internasional.
-
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi." Meskipun DUHAM tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, semangatnya condong pada perlindungan hak untuk hidup.
-
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR mengatur tentang hak untuk hidup. Ayat 2 Pasal 6 menyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan untuk "kejahatan yang paling serius" (most serious crimes) sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Ayat 6 Pasal 6 ICCPR juga mendorong negara-negara pihak untuk menghapuskan hukuman mati.
Debat muncul mengenai definisi "kejahatan yang paling serius." Komite Hak Asasi Manusia PBB (badan pengawas ICCPR) menafsirkan bahwa "kejahatan yang paling serius" harus memiliki karakter yang sangat ekstrem, seperti pembunuhan yang disengaja. Ini berarti kejahatan narkotika atau korupsi, meskipun berat, tidak selalu memenuhi kriteria ini dalam pandangan Komite HAM PBB. Indonesia, dalam hal ini, memiliki penafsiran yang lebih luas terhadap "kejahatan yang paling serius" sesuai dengan ancaman kejahatan di dalam negeri. -
Protokol Opsional Kedua ICCPR (ICCPR-OP2): Protokol ini bertujuan untuk penghapusan hukuman mati. Indonesia belum meratifikasi protokol ini, yang menunjukkan bahwa secara formal Indonesia belum berkomitmen pada penghapusan hukuman mati secara total.
-
Tren Global: Mayoritas negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati, baik secara hukum (abolisionis de jure) maupun dalam praktik (abolisionis de facto/moratorium). Indonesia, bersama dengan beberapa negara lain, termasuk dalam minoritas yang masih mempertahankan dan melaksanakan hukuman mati. Hal ini seringkali menimbulkan tekanan diplomatik dan kritik dari komunitas internasional.
IV. Argumen Pendukung dan Penentang Kebijakan Hukuman Mati
A. Argumen Pendukung (Retensionis):
- Efek Deterensi (Jera): Diyakini bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah individu lain untuk melakukan kejahatan serupa, khususnya kejahatan berat seperti terorisme dan narkotika yang berdampak luas.
- Retribusi dan Keadilan: Hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal (lex talionis) bagi korban dan keluarga korban kejahatan yang sangat keji.
- Perlindungan Masyarakat: Dengan mengeksekusi pelaku kejahatan ekstrem, negara memastikan bahwa individu tersebut tidak akan pernah lagi membahayakan masyarakat.
- Kedaulatan Negara: Bagi sebagian pihak, mempertahankan hukuman mati adalah bagian dari kedaulatan hukum suatu negara untuk menentukan sistem pemidanaannya sendiri tanpa intervensi asing.
B. Argumen Penentang (Abolisionis):
- Irreversibilitas dan Risiko Kesalahan: Hukuman mati adalah pidana yang tidak dapat dibatalkan. Risiko eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, meskipun kecil, selalu ada dan tidak dapat diperbaiki.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, serta melanggar hak asasi paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.
- Tidak Terbukti Efektif sebagai Deteren: Banyak penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti konklusif yang membuktikan bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang lebih tinggi dibandingkan pidana penjara seumur hidup.
- Potensi Diskriminasi: Penerapan hukuman mati seringkali bias dan diskriminatif, baik berdasarkan status sosial-ekonomi, etnis, maupun kemampuan akses terhadap keadilan. Individu dari latar belakang kurang mampu seringkali lebih rentan dijatuhi hukuman mati.
- Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi: Metode eksekusi, apa pun bentuknya, seringkali dianggap sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi.
- Peluang Rehabilitasi: Hukuman mati menghilangkan segala peluang bagi terpidana untuk direhabilitasi dan berintegrasi kembali ke masyarakat, atau setidaknya menunjukkan penyesalan.
V. Dilema dan Tantangan Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia
Kebijakan hukuman mati di Indonesia berada dalam persimpangan dilema antara kedaulatan hukum nasional, aspirasi keadilan masyarakat, dan komitmen terhadap hak asasi manusia universal.
- Keseimbangan Kedaulatan vs. Hukum Internasional: Indonesia harus menavigasi tuntutan untuk menghormati norma-norma hak asasi manusia internasional tanpa mengorbankan kedaulatan hukumnya dan kebutuhan untuk menanggulangi kejahatan berat di dalam negeri.
- Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Adanya hukuman mati menuntut sistem peradilan pidana yang sangat cermat, transparan, dan akuntabel. Setiap celah potensi kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan harus diminimalisir.
- Penerapan KUHP Baru: Implementasi "pidana mati alternatif" dalam KUHP Baru akan menjadi ujian penting. Keberhasilan mekanisme masa percobaan 10 tahun akan sangat bergantung pada evaluasi objektif terhadap perilaku terpidana dan ketersediaan program rehabilitasi. Ini bisa menjadi langkah awal menuju pengurangan, atau bahkan penghapusan, hukuman mati secara de facto.
- Edukasi Publik: Perdebatan tentang hukuman mati juga mencerminkan perbedaan pandangan di masyarakat. Edukasi publik tentang argumen pro dan kontra, serta konsekuensi hukum dan HAM, menjadi penting untuk mendorong dialog yang konstruktif.
Kesimpulan
Analisis yuridis terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang berlapis. Secara hukum positif, hukuman mati masih eksis dan diakui, bahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan hak untuk hidup sebagai hak yang dapat dibatasi oleh undang-undang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini terus-menerus dihadapkan pada kritik tajam dari perspektif hak asasi manusia internasional dan tren global menuju penghapusan.
Langkah maju dengan pidana mati alternatif dalam KUHP Baru menunjukkan adanya niat baik untuk beradaptasi dengan perkembangan HAM global, sekaligus tetap menghargai aspirasi keadilan masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam memastikan keadilan substantif, mencegah kesalahan fatal, dan menyeimbangkan kedaulatan hukum dengan komitmen kemanusiaan. Masa depan hukuman mati di Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan menghormati martabat manusia, di tengah dinamika domestik dan global yang terus berkembang.